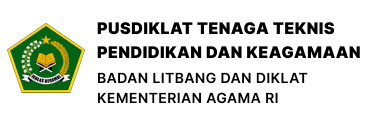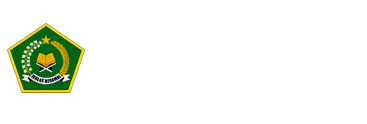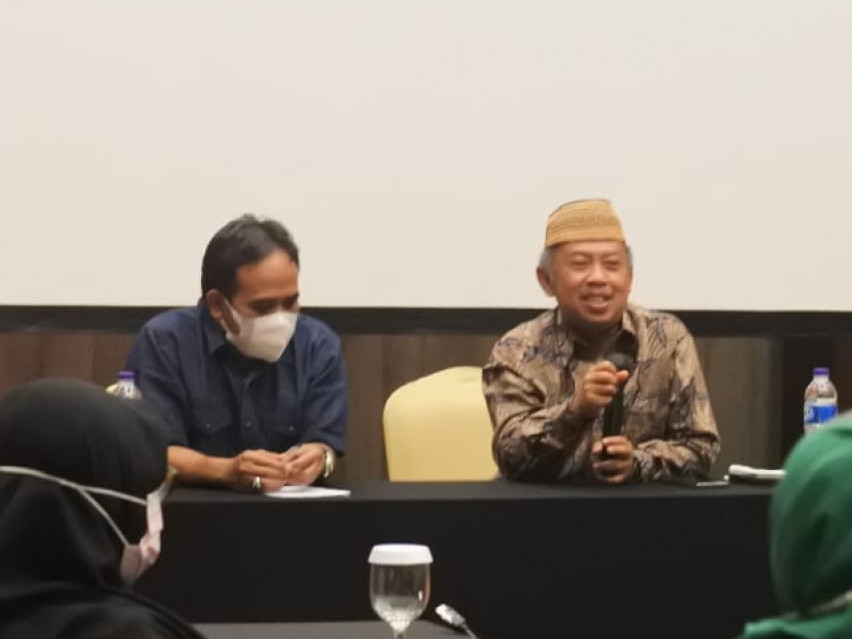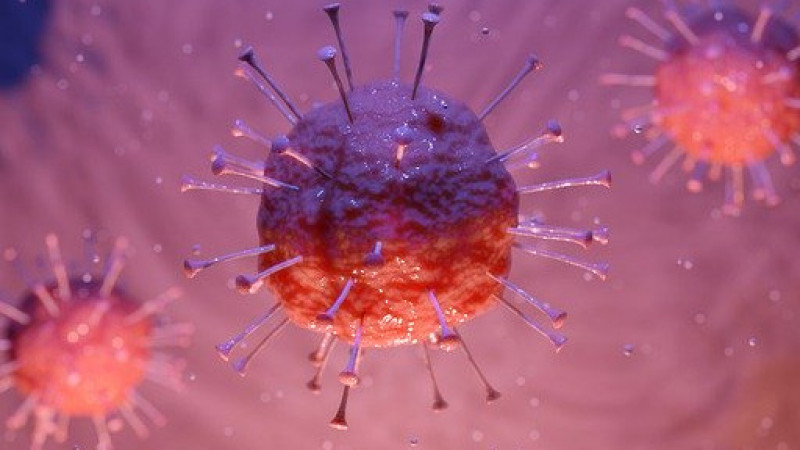
Wabah Corona dan Polisentris Indonesia
Saya justru memandang bahwa wabah virus yang saat ini melanda dunia, dan sedang menjalar juga di Indonesia, disikapi dengan sangat beragam bahkan dalam batas-batas tertentu “dualistik”.
Secara garis besar, mereka yang masuk dalam kategori “state-actors” tentu saja cenderung “strukturalis” seolah-olah apa yang telah menjadi suatu kebijakan negara itu secara ketat dan patuh harus diikuti dan terus menerus disebarkan kepada masyarakat.
Kelompok ini—kebanyakan—tentu saja para birokrat, pendukung pemerintah, kelompok pragmatis, agamawan-politis, atau “akademisi-birokratis” yang entah kebetulan atau tidak merupakan golongan menengah-keatas yang memiliki kecemasan akut terhadap pandemik yang horor itu.
Suara mereka tampak dominan di berbagai linimasa, bahkan tak tanggung-tanggung, tampak kontraproduktif jika dihadapkan kepada suatu pendewasaan yang lebih realistis dalam membangun kekuatan mentalitas masyarakat.
Alih-alih membuat masyarakat “religius” seperti Indonesia ini menjalin kekuatan solidaritas yang kuat, malah mencerai-beraikannya, bahkan menghantam dengan pukulan pemecah es balok yang seketika memporak-porandakannya. Mereka lebih berfungsi sebagai pemecah batu es dari pada menjadi gergaji yang membelah sebagian demi sebagian, lalu dipisahkan sesuai dengan kebutuhan.
Diluar itu, ada kelompok “non-state actors” yang memang memiliki beragam latar belakang, baik agama, politik, maupun ekonomi.
Kelompok ini tentu saja lebih memperlihatkan genre masyarakat menengah-kebawah, sebab mereka umumnya para agamawan-praktis, pemikir-idealis, akademisi-kritis, atau para pekerja biasa dalam sektor-sektor ril, atau masyarakat non-elitis yang tergabung dalam kelompok-kelompok tertentu yang “anti-politik”.
Anda bisa menyebut tipe-tipe kelompok yang lainnya yang mungkin saja bisa lebih banyak dari kategori yang telah saya sebutkan ini. Kelompok ini memiliki kecenderungan “fatalistik” dalam pengertian bahwa situasi negara yang tampak semrawut ini tak berpengaruh apapun bagi mereka sekalipun ada upaya-upaya tertentu dengan apa yang digenbar-gemborkan sebagai “jihad kemanusiaan”: sebuah adagium indah yang menggabungkan antara bahasa agama dan politik sekaligus dan menunjukkan betapa istilah ini ingin diakui sebagai pernyataan religius dan dapat dipahami dalam ranah masyarakat religius pula.
Saya menyebut “fatalistik” bukan berarti bahwa kecenderungannya benar-benar “pasrah dalam titik terendah”, namun lebih kepada ingin membangun kepercayaan diri (self-confidence) yang lebih kuat dan mandiri terlepas dari berbagai “dikte politik” yang merantai seluruh bangunan pemikiran dan keyakinan, padahal setiap manusia punya hak untuk mengekspresikan pemikiran dan pendapatnya.
Pada tahap ini, tampak dualisme “kepentingan” atau lebih jauh “kekuasaan” antara dua kekuatan yang saling berseberangan. Kita tentu tak harus heran dengan kondisi seperti ini, sebab inilah sesungguhnya cara pandang manusia terhadap dunia: dualistik.
Dalam sejarah Nusantara, kondisi ini telah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu dimana terdapat lusinan raja atau pangeran yang saling berperang sepanjang hampir dua abad.
Orang banyak menyangka Nusantara merupakan satu kesatuan politik dibawah kontrol satu kekuasaan kerajaan, ternyata tidak. Kita bisa melihat betapa banyaknya komplek candi dan prasasti bertebaran di seluruh penjuru pulau Jawa, padahal kerajaan terbesar Majapahit berada di antara reruntuhan desa Trowulan yang semestinya terpusat disana.
Belum kekuasaan Sumatera dan Bali yang hampir menunjukkan polisentris dalam kekuasaan Nusantara dan tidak lagi dualistik. Maka tak mengherankan, para sejarawan pada waktu itu merupakan korban “persekongkolan jahat” yang terdiri dari para filosof Cina atau India Kuno, serta penyalin naskah-naskah resmi yang menyembunyikan kebenaran sejarah.
Wabah Corona yang menjadi kecemasan masyarakat modern (modern risk society) ditanggapi secara beragam oleh masyarakat Indonesia dan barangkali terdapat keunikan tersendiri mengingan Indonesia merupakan cermin masyarakat religius sejak zaman dahulunya.
Sekalipun wabah ini telah terbukti secara empirik dan penyebarannya sangat rasional, tetapi tanggapan-tanggapan bersifat teologis bahkan mistis tetap muncul sebagai cara pandang alternatif, sebagai upaya mendukung kebijakan negara atau yang menolaknya.
Uniknya, kita seolah kembali ke masa-masa perdebatan awal pemikiran Islam antara ortodoks dan heterodoks, antara penganut klaim “ahlu sunnah” dan “ahlu bidah” yang saling bertentangan secara kontradiktif.
Yang “bidah” malah sekarang muncul sebagai “sunah” bahkan sebaliknya demi kepentingan kelompoknya masing-masing, bukan demi kepentingan kemaslahatan bersama. Kita dikejutkan oleh munculnya “pembenaran” teologis yang didukung ayat-ayat al-Quran maupun hadis, sekalipun pada awalnya mereka bukanlah kalangan literalis atau tekstualis pengikut setia Ibnu Taimiyyah, tetapi yang mereka sodorkan adalah teks-teks keagamaan yang digali dan dicari untuk sekadar mendukung klaim kebenaran penguasa.
Saya cenderung menghindar untuk memunculkan aspek teologis tertentu dalam membaca situasi yang mencekam saat ini, kecuali hal-hal tertentu yang mengingatkan pada “siapa kita” sebelum isu menakutkan ini melanda Nusantara.
Nenek moyang kita yang hidup ratusan tahun yang lalu sudah terbiasa dengan pluralisme dan hampir-hampir tak ada satu kekuatan politik besar yang dapat mendikte keseluruhan masyarakat Nusantara.
Kita juga tak perlu heran ketika ada dua kerajaan di Nusantara yang bersumpah untuk saling memusuhi, tetapi di sisi lain saling menasihati tentang aktivitas orang-orang Eropa yang yang dapat mengancam kesejahteraan wilayahnya masing-masing.
Inilah yang sejak dahulu membuat orang-orang Eropa bingung, padahal mereka telah sejak lama menginginkan Nusantara ini bercorak monarki sebagaimana ajaran politik yang diperkenalkan pada waktu itu kepada para raja Nusantara. Dulu orang Eropa kebingungan terhadap Nusantara, sekarang justru terbalik, kita dibingungkan oleh orang-orang Eropa dan Nusantara kebingungan.
Sedikit sebuah catatan yang saya kutip dari sejarawan asing yang meneliti tentang Indonesia:
“penghuni pulau-pulau itu tidak tunduk pada hukum, raja, atau tuan manapun…Mereka yang memiliki budak paling banyak dan terkuat, bisa memperoleh apapun yang diinginkannya…Mereka tidak mengakui raja atau pemerintah dan budak-budak merekapun tidak tunduk secara penuh kepada tuan dan raja mereka…”
Jadi, anda dapat menafsirkan sendiri bahwa kita ini tinggal di Nusantara yang sangat plural, sangat religius, sangat beragam, dan secara politik “polisentris” sehingga wajar jika muncul berbagai perbedaan pendapat yang tidak seharusnya disamakan dengan masyarakat Italia, Arab, Amerika, atau lain-lainnya.
Nusantara punya kekhasan, mereka masih memiliki matarantai tradisi yang sangat kuat, bahkan sebagaimana digambarkan Gertz, masyarakat Nusantara dibangun melalui jaringan yang kompleks kekerabatan dan hubungan pribadi yang sering ditunjang oleh legitimasi supranatural.
Kita ini keturunan “orang-orang sakti” yang kadang sulit dimengerti tetapi justru hubungan-hubungan rumit inilah yang sesungguhnya menyatukan, meleburkan, mengentalkan, seluruh cara pandang berbeda dan berpikir yang tidak kita dapatkan dalam model masyarakat manapun. Inilah Indonesia, yang kuat, hebat, dan tahan lama! (Sahirul Alim)
Sumber: kompasiana.com