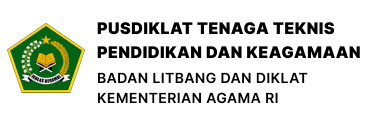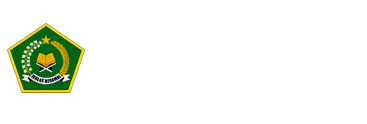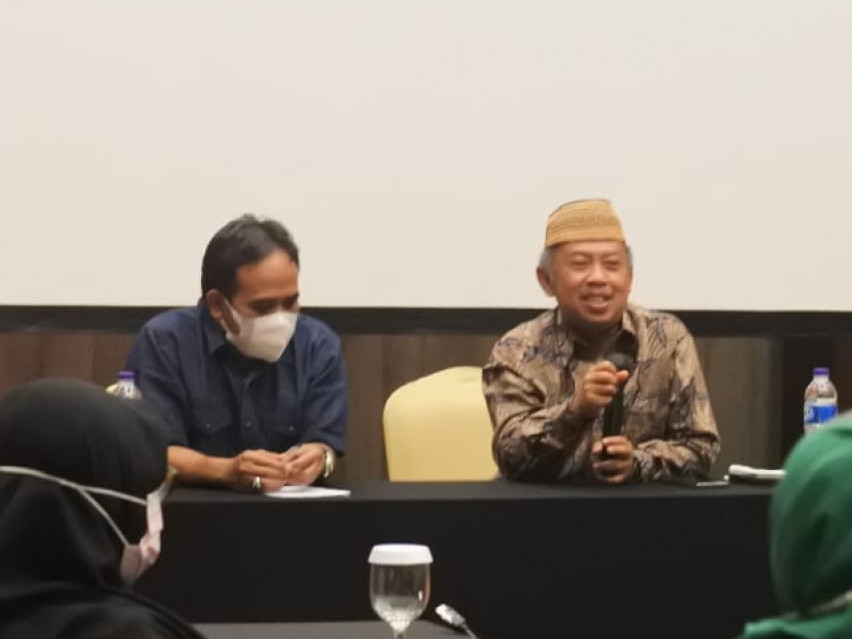Ketika Manusia Berjumpa Tuhan: Spirit Isra dan Mi’raj Nabi Muhammad SAW
Salah satu puncak spiritualitas manusia adalah bertemu langsung dengan Yang Menciptakannya, yaitu Tuhan. Pertemuan ini adalah entitas paling tinggi dari seluruh esensi kehidupan manusia dan hal inilah yang dicari oleh siapapun, termasuk yang paling tampak bagaimana para sufi atau mistikus mengelaborasi teori-teori tertentu yang menggambarkan realitas pertemuan dengan Tuhan. Teori emanasi atau monisme yang dibawa para sufi abad pertengahan, seperti al-Hallaj, Suhrawardi, atau Ibu Arabi jelas menunjukkan bagaimana mengolah aspek spiritual secara lebih tegas: penyatuan dengan alam raya dan pada puncaknya penyatuan dengan sang Maha Pencipta.
Berbagai teori gnosis yang barangkali merefleksikan filsafat yang rasional-empirik dan tasawuf yang transendental-mistik mendapatkan momentumnya pada aras “penyatuan” dimensi kemanusiaan dan dimensi Ketuhanan. Sulit memang merasionalisasikan berbagai teori gnosis ini, namun bahwa ajaran-ajarannya yang unik dan spekulatif sangat menarik untuk didiskusikan. Saya tentu tidak mendiskusikan persoalan tersebut, karena dalam hal ini, saya ingin menyatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi’raj Nabi Muhammad merupakan entry point yang dipergunakan oleh para mistikus Muslim mengelaborasi lebih jauh tentang teori-teori mistiknya.
Peristiwa Isra dan Mi’raj Nabi Muhammad SAW jelas diabadikan dalam Al-Quran, bahkan diperkuat oleh beberapa hadis yang secara genealogi inetelektualnya menduduki status “terpercaya”. Kita tentu saja tak perlu mempertanyakan apakah peristiwa ini rasional atau tidak rasional, terlebih terdapat perdebatan apakah Nabi Muhammad melakukannya dalam kesadarannya (ruh dan jasadnya) atau hanya peristiwa spiritual (hanya ruh saja) ketika Nabi melakukan perjalanan hanya kurang dari satu malam, berjalan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsha di Ilia, Palestina. Kemudian disusul dengan “naiknya” beliau ke “Sidratul Muntaha”—suatu tempat tak berujung, sehingga seolah-olah inilah representasi “tempat terakhir” dari tempat apapun yang ada di dunia. Bagi saya, ini merupakan mukjizat Tuhan yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, sehingga setiap mukjizat tak membutuhkan rasio untuk mengukurnya kecuali keyakinan bahwa mukjizat diberikan kepada manusia tertentu yang memiliki kedekatan khusus dengan Tuhannya.
Isra dan Mi’raj adalah peristiwa luar biasa, fakta dan bukan fiksi sebagaimana yang juga banyak dinilai oleh kalangan rasionalis. Faktual, sama seperti peristiwa lahirnya Isa AS tanpa ayah dari rahim Maryam RA atau Adam AS sebagai manusia pertama yang bahkan tidak “dilahirkan” tetapi langsung diciptakan oleh Tuhan dari sari pati tanah. Akal manusia tentu sangat terbatas, sehingga wajar ketika rasionalisasi lahir di Barat pada abad ke-16 tidak bertahan lama dan digantikan oleh cara pandang empirik yang tidak selalu positivistik. Empirisisme tidak selalu didasarkan oleh cara pandang rasional dengan ukuran-ukuran wajar, namun empiris juga merupakan bagian dari pengalaman individual yang justru lebih objektif karena mengalami langung setiap peristiwa tertentu lalu “diterjemahkannya” kedalam realitas-realitas empirik yang rasional. Etika, merupakan entitas lain yang mengontrol rasionalisme, sehingga ukuran-ukuran kebenaran dibaca melalui standar etika, setelah melalui penalaran rasional par excellence.
Membaca peristiwa Isra dan Mi’raj berarti membaca agama yang erat kaitannya dengan etika, bukan semata-mata peristiwa ilmiah yang diukur melalui standar rasio yang terbatas. Dalam tradisi ilmiah modern, terdapat sesuatu yang tak dapat dijangkau akal, yaitu “fenomena” dimana menurut persepsi Rudolf Otto bahwa peristiwa atau pengalaman keagamaan memuat sebuah “numena” (yang suci) yang harus ditetapkan sebagai suatu “sui generis”, meskipun tidak sesuai dengan kriteria rasional. Melalui pendekatan fenomenologis atas berbagai peristiwa keagamaan tertentu, maka kita dapat memberikan ukuran-ukurannya secara “objektif” dengan melibatkan kerangka “subjektivitas” dari orang-orang yang beriman.
Hampir dipastikan bahwa manusia pada dasarnya cenderung ke arah spiritual dibandingkan yang material, terlebih melihat tren sejarah manusia di abad ke-21 ini. Di hampir seluruh negara, tidak ada yang mengesampingkan aspek religius dalam pengertian formal, bahkan seluruh aturan negara, kebijakan pemerintah yang tertulis dalamn undang-undang tetap menyebutkan agama atau “spirit” sebagai bagian dari kehidupan bernegara. Terutama sumpah presiden yang hampir di negara manapun selelu melibatkan nama Tuhan didalamnya dan simbol kitab suci yang dihadirkan, bukanlah pelengkap sumpah tetapi satu hal yang tak bisa ditawar-tawar. Tidak ada manusia yang benar-benar “atheis” atau “mengingkari adanya Tuhan”, paling tidak, sekalipun mereka bersikap agnostik, kita tidak pernah tahu dan mengukur sejauh mana “keingkaran” mereka terhadap seluruh keteraturan alam raya ini dan pada akhirnya meyakini dalam hati kecilnya, bahwa ada sebuah kekuatan yang tak terlihat yang mengatur ritme dan harmonisasi denyut kehidupan alam semesta.
Sebagai Muslim, saya selalu diingatkan akan sebuah peristiwa luar biasa, peristiwa fenomenologis yang hanya dipahami oleh pendekatan iman, bahwa peristiwa Isra dan Mi’raj yang dialami pribadi agung Nabi Muhammad SAW merupakan hal yang juga dapat dialami oleh setiap manusia dengan cara atau bentuk yang berbeda-beda. Perjalanan Nabi dari Mekah ke Yerussalem, menunjukkan aspek spiritualitas dalam memuaskan kehidupan beragama, melihat bahwa Mekah dengan simbol “Ka’bah” yang menjadi kiblat umat Muslim di dunia, hendaknya tidak melupakan realitas agama Tuhan sebelumnya dimana simbol suci itu ditunjukkan melalui Baitul Maqdis di Palestina, sebuah entitas kesucian agama dalam tradisi Yahudi-Kristen yang juga bagian dari tradisi Islam. Majid al-Aqsha tentu saja pernah menjadi kiblat umat Muslim selama berabad-abad, sebelum kemudian pada kira-kira 623 M, Nabi Muhammad mengubahnya ke arah Ka’bah sebagai kiblat baru umat Muslim. Melalui peristiwa Isra ini kita lebih diajak pada suasana spiritual keagamaan secara lebih toleran, dimana terdapat tradisi-tradisi atau agama-agama lain yang hidup secara berdampingan.
Puncak spiritualistas yang paling tinggi adalah pertemuan manusia dengan Tuhan dan ini merupakan bagian inheren dari seluruh ajaran agama manapun. Konsep “pertemuan” ini paling inti dalam ajaran Islam sebagaimana dielaborasi dalam konsep Tauhid, dimana konsep ini lebih sering berkonotasi “penyatuan” antara manusia dengan Tuhan, daripada sekadar “pengakuan” terhadap eksistensi Tuhan Yang Maha Tunggal. Sebagai manusia agung yang terpilih, Nabi Muhammad diizinkan untuk melakukan “mi’raj” bertemu langsung dengan Tuhan dan ini merupakan esensi dari seluruh ajaran Tauhid yang dikembangkan dalam aspek teologi Islam.
Perjumpaan Nabi dengan Tuhan ini menghasilkan sebuah “kesepakatan” yaitu praktik ritual bagi setiap Muslim yang dikenal dengan “sholat” dimana dalam pengertian leksikalnya adalah “doa”. Salat, merupakan sarana bagi setiap Muslim untuk “naik” (mi’raj) untuk bertemu secara spiritual dengan Tuhan dan hampir tidak ada ritual sejenis yang mampu meningkatkan spiritualitas seorang Muslim, kecuali ketika dia melaksanakan, memahami, bahkan mengaktualisasikan setiap salatnya. Salat merupakan entitas tertinggi dari puncak spiritualitas seorang Muslim, yang aktualisasi sebenarnya berupa nilai-nilai kemanusiaan yang paling hakiki: salat akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika manusia mencapai puncak spiritualitasnya melalui kesempurnaan salat, maka tak akan ada keburukan diluar dirinya, sebab nilai spiritualitas senantiasa mengajaknya kepada kebaikan dan kemaslahatan. (Sahirul Alim)
Sumber: kumparan.com