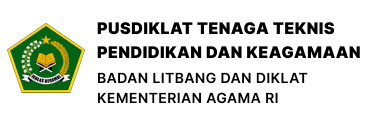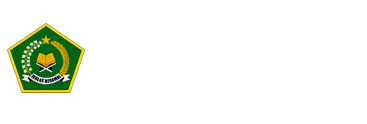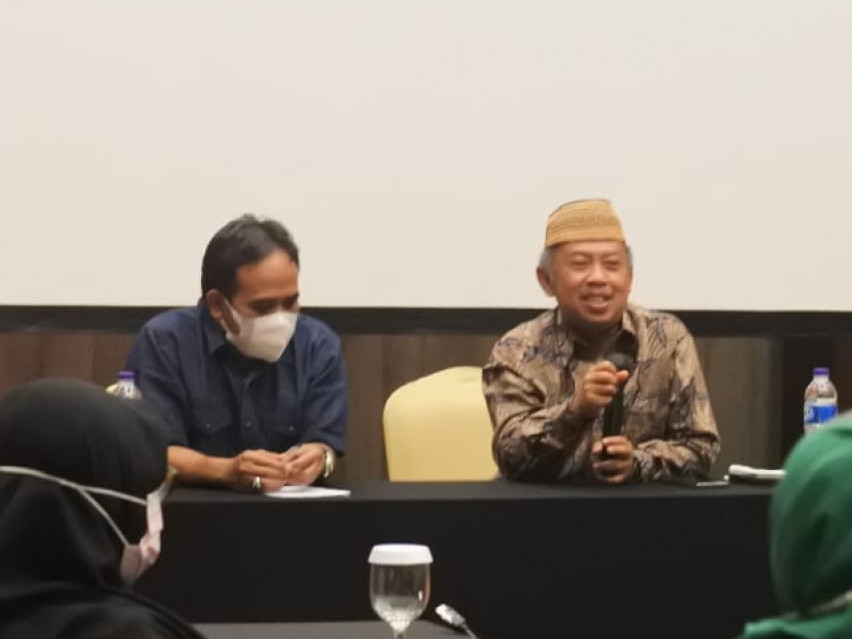Haji dan Kesalehan Sosial
Haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang pelaksanaannya ditentukan (asyhurun ma’lumaat) wajib dilaksanakan oleh setiap orang beriman. Karena pelaksanaannya di bulan-bulan yang telah ditentukan, kemudian muncul berbagai pendapat diantara para ulama, apakah haji merupakan kewajiban “kontan/segera” (faur) atau “boleh ditunda/pilihan” (tarakhi). Pendapat sebagian besar ulama, ibadah haji adalah ibadah “pilihan” yang boleh diundur pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi kesiapan dan kemampuan (istitho’ah) seseorang. Prinsip ibadah tentu saja memudahkan dan bukan memberatkan, sehingga kondisi-kondisi tertentu—terutama terkait dengan haji—terkait erat dengan kondisi kesiapan fisik, materi, dan juga psikis seorang jamaah.
Kewajiban haji dan umrah yang dilaksanakan bersamaan di bulan Dzulhijjah, didasarkan pada ayat 196 surat al-Baqarah:
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
“Dan sempurnakanlah (kewajiban) haji dan umroh karena Allah..”
Ayat diatas kemudian ditafsirkan secara berbeda oleh para ulama , sebagaimana dijelaskan diatas. Namun, menurut Imam Syafii dan juga sahabat yang lainnya ayat ini turun kepada Rasulullah setelah hijrah. Sedangkan, Rasulullah sendiri baru “membuka” Mekah (fathu makkah) pada sekitar tahun ke 8 H di bulan Ramadan. Setelah peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah dan umat muslim banyak disibukkan oleh berbagai peristiwa peperangan, diantaranya perang Tabuk dan Hunain. Hampir selama 2 tahun kondisi tidak memungkinkan untuk pelaksanaan haji, maka baru pada tahun 10 H, Rasulullah dan seluruh umat muslim menunaikan ibadah haji yang dikenal dengan “Haji Wada”.
Dalam beberapa catatan sejarah, pelaksanaan haji Rasulullah hanyalah satu kali, disaat Haji Wada’, sedangkan umroh beliau hanya dilaksanakan 3 kali yang keseluruhannya dilakukan pada bulan-bulan haji, 3 kali dilakukannya pada bulan Dzulqa’dah dan 1 kali di bulan Dzulhijjah. Itulah kenapa ada anggapan bahwa haji kewajibannya hanya satu kali, sedangkan jika mampu haji yang berikutnya bersifat “tathowwu’” (suka rela). Terlebih jika dikaitkan dengan keberadaan haji di Indonesia yang harus rela mengantri selama bertahun-tahun, sehingga persepsi soal haji sekali seumur hidup menjadi kewajiban yang tak bisa ditawar-tawar.
Haji erat kaitannya dengan kesalehan sosial, mengingat ketika seseorang telah berniat untuk haji terdapat larangan-larangan tertentu, seperti berbicara kasar atau buruk (rafats), berbuat dosa dan maksiat (fusuq), dan berselisih pendapat atau berdebat yang tidak perlu (jidaal). Keseluruhan larangan ini sesungguhnya memberikan pemahaman, betapa setiap orang dalam lingkungan sosialnya tak mungkin dilepaskan dari ketiga kondisi tersebut (rafats, fusuq, dan jidaal). Haji, memberikan pelajaran penting agar setiap orang mampu meninggalkan ketiga sifat buruk tadi dan benar-benar dapat berpengaruh baik dalam lingkungan sosialnya.
Hal ini dijelaskan dalam al-Quran, bahwa larangan-larangan tersebut—terutama bagi yang berhaji—harus dihindari karena akan berdampak pada kemabruran haji seseorang. Dalam ayat 197 al-Baqarah dijelaskan:
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ
“Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji”.
Cara memperoleh predikat haji mabrur tentu saja menghindari seluruh larangan selama berhaji dan ciri seseorang yang menjadi mabrur hajinya jelas melepaskan seluruh keburukan sebagaimana yang telah dihindarinya selama berhaji. Dengan demikian, ciri seseorang yang mabrur hajinya adalah tidak lagi berkata rafats, selalu menjauhi hal-hal buruk bagi diri dan lingkungannya atau terhindar dari fasiq, sekaligus hampir dipastikan selalu menjauhi perdebatan atau perselisihan yang dirasa tidak bermanfaat. Itulah sebabnya, Rasulullah menjamin bahwa seseorang yang mendapat predikat haji mabrur adalah mereka yang setelah kembali ke tanah air, seperti bayi yang baru lahir. Dalam suatu riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda:
من حج هذا البيت فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه
“Siapa yang berhaji ke Baitullah, lalu tidak melakukan rafats (berkata-kata kotor atau kasar) dan tidak pula berbuat dosa dan maksiat (fasiq), maka ia akan kembali seperti hari dimana dirinya dilahirkan oleh ibunya”.
Hanya dua ibadah yang disebutkan menjadi “kifarat” (penghapus dosa) yang ketika sempurna dijalankan, tak ubahnya seseorang itu kembali suci dan bersih seperti bayi yang baru dilahirkan, yaitu puasa dan haji. Namun, yang paling erat kaitannya dengan wujud kesalehan sosial, hanyalah haji mabrur. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis hasan:
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ»، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا بِرُّ الْحَجِّ الْمَبْرُورُ؟ قَالَ: «إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ
“Dari Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda: Haji mabrur itu tak ada pahala baginya kecuali surga. Lalu para sahabat bertanya: Wahai Nabi Allah, apa itu haji mabrur? Lalu Nabi menjawab: ‘berikanlah makanan/sedekahlah dan tebarkanlah kedamaian” (HR Bukhari, Ahmad, Hakim, Baihaqi).
Kalimat “bersedekah” dan “menebarkan perdamaian atau salam” adalah wujud nyata dari kesalehan sosial karena kepedulian seseorang terhadap lingkungan sosial untuk peduli, berbagi, menebarkan kedamaian, dan menjauhi keburukan. Seluruh proses pembentukan kesalehan sosial sangat terlihat dalam seluruh ritualisasi haji yang memiliki pemaknaan tersendiri. Kain ihram yang dikenakan selama menjalankan rukun haji, pertanda pakaian sosial yang hanya menempel di tubuh tanpa berjahit dan semua sama berwarna putih. Hal ini mengindikasikan, seluruh sifat keduniaan yang melekat, baik kekayaan, status sosial, pangkat, atau jabatan dilepaskan dan semua sama dihadapan Allah tak ada perbedaan. Haji merupakan pelajaran sangat penting dalam menata kehidupan sosial agar menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih sempurna, baik dalam konteks hablumminallah dan hablumminannaas. Wallahu a’lam bisshawab.