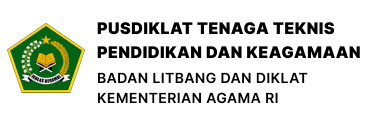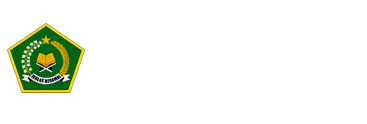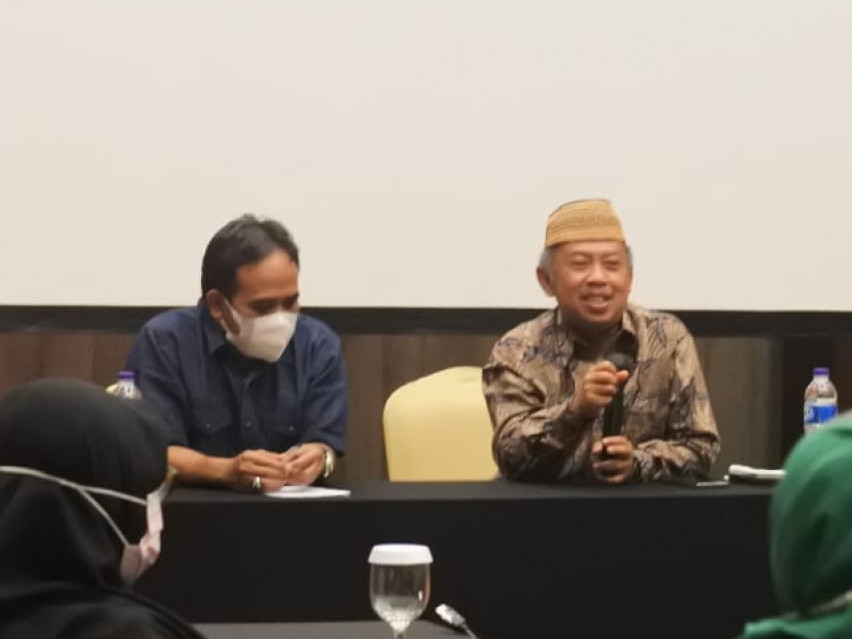Islam Indonesia: Dialektika, Resepsi, dan Negosiasi
Suatu saat ketika saya berjalan di suatu kampung di wilayah pesisir Jawa Timur, hampir setiap orang yang saya temui selalu menyapa atau minimal melemparkan senyum tanpa terpaksa.
Di salah satu tempat pelelangan ikan di Dusun Karanji, Paciran, Lamongan, saya berhenti sejenak memperhatikan beberapa orang yang bersemangat menimbang hasil tangkapan ikannya dan menghitung uang hasil dari keuntungan menjualnya.
Sambil bekerja, tampak ungkapan-ungkapan mereka yang mungkin agak mencengangkan: mereka bercerita tentang makam Sunan Drajat yang harus dikunjungi atau menggelar slametan atas setiap hasil yang mereka peroleh sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan.
Keterikatan mereka terhadap warisan budaya atau tradisi, seolah tak pudar ditengah gempuran arus reformisme Islam yang sedemikian hebat menangkal tradisi-tradisi lokal.
Beberapa waktu yang lalu, saya berada di Mekah dan melakukan hal yang sama, berjalan menyusuri jalanan kota yang penuh dengan kendaraan yang dibuat oleh pabrikan asal Jepang maupun Korea. Hampir tak ada kata sapaan atau kekadar senyuman, kecuali para pedagang atau supir taksi yang tiba-tiba berhenti menawarkan jasa bisnisnya.
Negeri yang dikenal sebagai “poros” Islam ini –karena memang Islam lahir di Arab– ternyata memberikan kesan yang sama sekali berbeda dengan banyak ceritera-ceritera yang saya baca dari berbagai riwayat Nabi Muhammad.
Ada suatu pergeseran budaya yang cukup jauh, bahkan seolah menjauhi porosnya sendiri, yang mana Islam yang digambarkan sedemikian ramah, ternyata tidak selalu berasal dari negeri yang disebut sebagai pusat sebarannya.
Cerita di atas, mungkin saja tak ada yang luar biasa, kecuali ketika kita membaca ulang karya-karya sejarawan Belanda yang memotret Islam di Indonesia secara lebih jujur. G.W.J. Drewes, dalam salah satu artikelnya, “Indonesia: Mistisisme dan Aktivisme” yang terbit pada 1955 seolah menyuguhkan hal yang kurang lebih sama.
Kesan pertama yang ia tuliskan bahwa kedudukan Islam di dalam masyarakat Indonesia kelihatan sederhana, bahkan hampir-hampir tak ada ciri yang menonjol, kecuali kesederhanaannya itu. Siapa saja yang telah mengenal Islam seperti di Afrika Utara atau Timur Tengah, kemudian mengunjungi Indonesia, selalu hampir tidak akan pernah percaya, bahwa ia betul-betul sedang berada di suatu negeri Islam.
Drewes melanjutkan, bahwa tidak hanya para pengunjung yang sekadar lewat ke negeri ini, bahkan para penduduknya yang sudah lama tinggal di Nusantara ini akan lebih banyak berceritera tentang Borobudur dan Candi-candi Hindu-Jawa, tentang tarian-tarian, dan pementasan-pementasan kesenian, atau bahkan tradisi-tradisi lokal lainnya yang hampir sama sekali tidak menyentuh aspek-aspek keislaman sebagaimana yang dibayangkan ketika di Timur Tengah.
Menariknya, belum tentu mereka mengetahui detil suatu masjid di wilayahnya yang seringkali menjadi bangunan-bangunan yang kurang perhatian, bahkan mungkin masih banyak langgar-langgar kecil yang tidak memiliki perabotan apapun didalamnya. Mungkin di daerah-daerah terpencil, negeri yang dianggap sebagai “daar al-islam” ini tak nampak sedikitpun secara lahiriyah replika peradaban Islam yang saat itu sedang mengalami kejayaan gemilang.
Sulit untuk tidak mengatakan, bahwa sesungguhnya, sekalipun Islam Indonesia tak terdampak langsung penetrasi peradaban dunia Islam, namun Islam amat dalam menguasai batin manusia Indonesia.
Laporan dari seorang Indonesianis dan Islamis kenamaan, Snouck Hurgronye, ketika menulis disertasinya mengenai Haji Indonesia, menulis bahwa kemenangan yang dicapai Islam di daerah-daerah Indonesia, setaraf dengan kejayaan agama ini secara keseluruhan di abad-abad sebelumnya.
Kejayaan Turki Utsmani yang melesat melewati batas ekspektasinya sebagai penguasa dunia Islam di Timur Tengah, ternyata seiring dengan peradaban Islam yang terbentuk di seluruh kepulauan Nusantara.
Suatu kejayaan atas Islam di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, tak lalu diartikan secara sempit bahwa Islam benar-benar tegak sesuai dengan realitas masa awalnya, di mana Nabi Muhammad dan para pengikut setianya masih hidup.
Hampir dipastikan, bahwa kejayaan Islam di mana pun tak pernah secara sempurna berhasil mengikis habis ide-ide pra-Islam sampai ke akar-akarnya. Malah sebaliknya, di mana-mana ada sesuatu yang lama yang tetap tinggal bahkan abadi dan di sisi lainnya, ide-ide bahkan lembaga pra-Islam itu masih dapat dilihat dan hidup (survive) dalam suatu komunitas masyarakat tertentu yang sudah “muslim”.
Wajah Islam Indonesia yang ditunjukkan oleh realitas masa lalunya, bahkan hingga kini sulit untuk tidak dilepaskan dari suatu dialektika budaya yang terus menerus dan menghasilkan suatu peradaban hakiki yang paripurna. Kesatuan religius dalam alam pikiran orang-orang Indonesia dengan berbagai warisan tradisinya meresap terlebih dahulu bahkan jauh melampaui nilai-nilai ideologinya sendiri.
Hal inilah barangkali yang menjadi perhatian Marshall G Hudgson dalam studinya tentang peradaban Islam, yang mana secara cermat ia menulis bahwa kesatuan ini telah membawa serta banyak, meskipun tidak semua, segi-segi kebudayaan yang dalam beberapa konteksnya mungkin tidak dipandang “religius”.
Hurgronye bahkan berhenti pada suatu kesimpulan, dimana kesatuan religius yang telah hidup dalam masyarakat muslim Indonesia pada akhirnya lebih menekankan aspek berpikir dibandingkan bertindak.
Kenyataan ini telah membawa dampak langsung, dimana resepsi Islam atas nilai-nilai tradisi lokal ditengah masyarakat telah mengalami adaptasi melalui aktivitas berpikir dengan mengedepankan “rasa” ketika mewujudkan tindakan Islam-nya.
Hal ini jelas berbeda dengan beberapa anggapan, bahwa Islam Indonesia lebih diwarnai oleh praktik-praktik (ritual) yang dipandang tidak mencerminkan “religiusitas” ketika praktik tradisi lokal dianggap “menyimpang” bahkan bukan berasal dari tindakan murni “Islam”.
Itulah sebabnya, kebanyakan masyarakat Indonesia termasuk dalam kategori penganut mazhab Syafi’i dan ritualitasnya mengikuti metode an-Nawawi dikarenakan ada aktivitas nalar yang sebelumnya hidup dan ortodoksi Syafi’i tentu saja dibangun oleh relasi-relasi dialektik yang mengedepankan nalar terlebih dahulu sebelum menentukan suatu tindakan hukum.
Kesesuaian dengan Syafi’iyah, tentu saja bukan pada aktivitas taqlid-nya, melainkan pada metode berpikirnya yang senantiasa bernegoisasi dengan kenyataan budaya lokal yang dihadapinya. Terdapat celah yang perlu dipelajari dan diteliti lebih jauh dalam hal ini, yang tentu saja membutuhkan berlembar-lembar halaman untuk menjelaskan bukti-bukti kesesuaiannya.
Memang, sekalipun ide-ide reformis Islam yang terutama berasal dari Mesir atau mengalirnya apa yang dijelaskan banyak pengamat sebagai ide “transnasional” Islam dalam pergumulan wacana Islam di Indonesia, tak pernah merubah sedikitpun soal dialektika, resepsi, dan negosiasi yang serta merta memberikan kekhasan terhadap Islam di Indonesia. Betapapun kuatnya arus ide-ide reformis atau modernis yang ingin mengubah wajah “Islam” Indonesia yang disesuaikan dengan apa yang ada dalam pikiran mereka, hanyalah upaya yang mungkin sia-sia belaka.
Kesatuan religius masyarakatnya dan sebagian hukum dan adat, umumnya telah bercampur menjadi suatu kesatuan tunggal, dianggap oleh masyarakat Indonesia berjalan dengan baik, sehingga keseimbangan yang benar-benar telah dicapai berabad-abad ini, tidak mudah diganggu atau diubah!